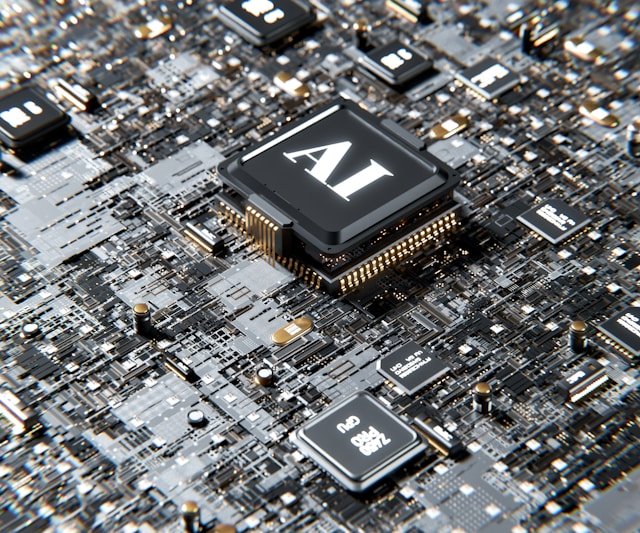JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Lampu sorot Hollywood sempat padam dalam waktu yang lama. Ribuan penulis dan aktor turun ke jalanan, membawa papan protes dengan wajah geram. Aksi mogok kerja SAG-AFTRA ini bukan sekadar menuntut kenaikan upah.
Sebaliknya, mereka sedang bertarung demi kelangsungan hidup profesi mereka. Musuh mereka kali ini tidak berwajah, tidak bernapas, dan tidak butuh tidur. Musuh itu adalah Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Pekerja seni merasakan ancaman eksistensial yang nyata. Pasalnya, teknologi kini mampu meniru wajah, suara, dan kreativitas manusia dengan tingkat kemiripan yang menakutkan.
Mimpi Buruk “Digital Replica”
Isu paling panas menyangkut hak atas wajah dan suara. Studio film mengajukan proposal yang terdengar seperti episode serial Black Mirror.
Mereka ingin memindai wajah aktor figuran (background actors), membayar mereka untuk satu hari kerja, lalu memiliki hak cipta atas versi digital mereka selamanya.
Akibatnya, studio bisa menggunakan “replika digital” aktor tersebut di film apa pun tanpa perlu membayar lagi. Tentu saja, para aktor menolak keras.
Mereka menganggap ini sebagai pencurian identitas. Lebih parah lagi, teknologi deepfake bisa menghidupkan kembali aktor yang sudah meninggal atau memanipulasi suara aktor hidup untuk mengucapkan hal-hal yang tidak pernah mereka setujui.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
ChatGPT Menggantikan Penulis Naskah?
Ketakutan serupa menghantui para penulis skenario. Eksekutif studio mulai melirik efisiensi yang ditawarkan oleh Large Language Models (LLM) seperti ChatGPT.
Mereka membayangkan masa depan di mana AI menulis draf awal skenario dalam hitungan detik. Kemudian, manusia hanya bertugas sebagai “tukang edit” yang memoles naskah robot tersebut dengan upah murah.
Padahal, menulis adalah proses kreatif yang rumit. Penulis menuangkan pengalaman hidup, trauma, dan harapan mereka ke dalam cerita. Lantas, jika mesin mengambil alih proses ini, orisinalitas cerita akan mati. Industri hanya akan mendaur ulang ide lama yang ada di database algoritma.
Pertanyaan Filosofis: Di Mana “Jiwa” Seni?
Perdebatan ini menyentuh ranah filosofis yang mendalam. Bisakah seni memiliki “jiwa” jika penciptanya adalah algoritma?
AI bekerja berdasarkan probabilitas statistik. Ia memprediksi kata atau piksel berikutnya berdasarkan data masa lalu. Artinya, AI tidak memiliki pengalaman batin. Ia tidak pernah merasakan patah hati, kehilangan, atau kebahagiaan.
Seni sejati lahir dari penderitaan dan pengalaman manusiawi (human experience). Oleh karena itu, karya yang dihasilkan mesin mungkin terlihat sempurna secara teknis, namun terasa kosong dan hampa secara emosional.
Regulasi Harga Mati
Pada akhirnya, kita tidak bisa menghentikan laju teknologi. Akan tetapi, kita wajib mengaturnya dengan ketat. Regulasi menjadi harga mati untuk melindungi hak cipta dan hak asasi manusia.
Pemerintah dan serikat pekerja harus memastikan bahwa teknologi hadir sebagai alat bantu (tool), bukan pengganti (replacement). Ingatlah, efisiensi tidak boleh menghapus kemanusiaan. Seni adalah benteng terakhir ekspresi jiwa kita yang tidak boleh kita serahkan begitu saja kepada kode biner.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia